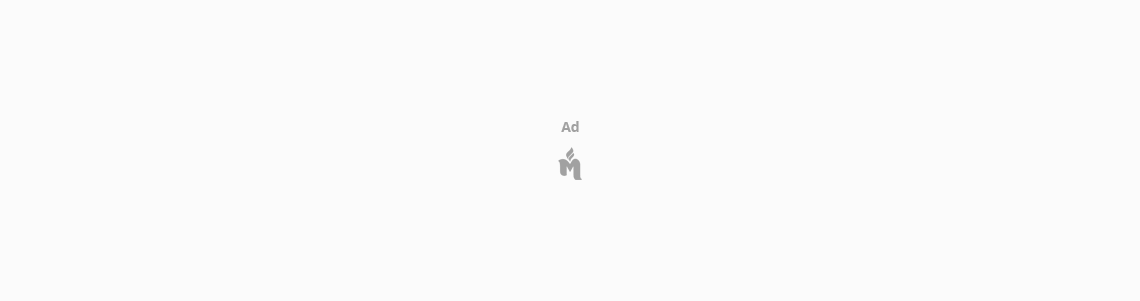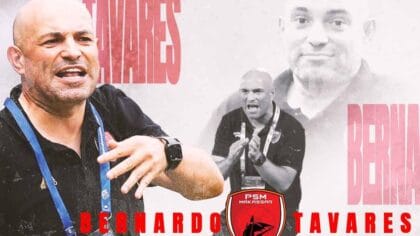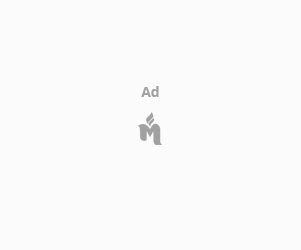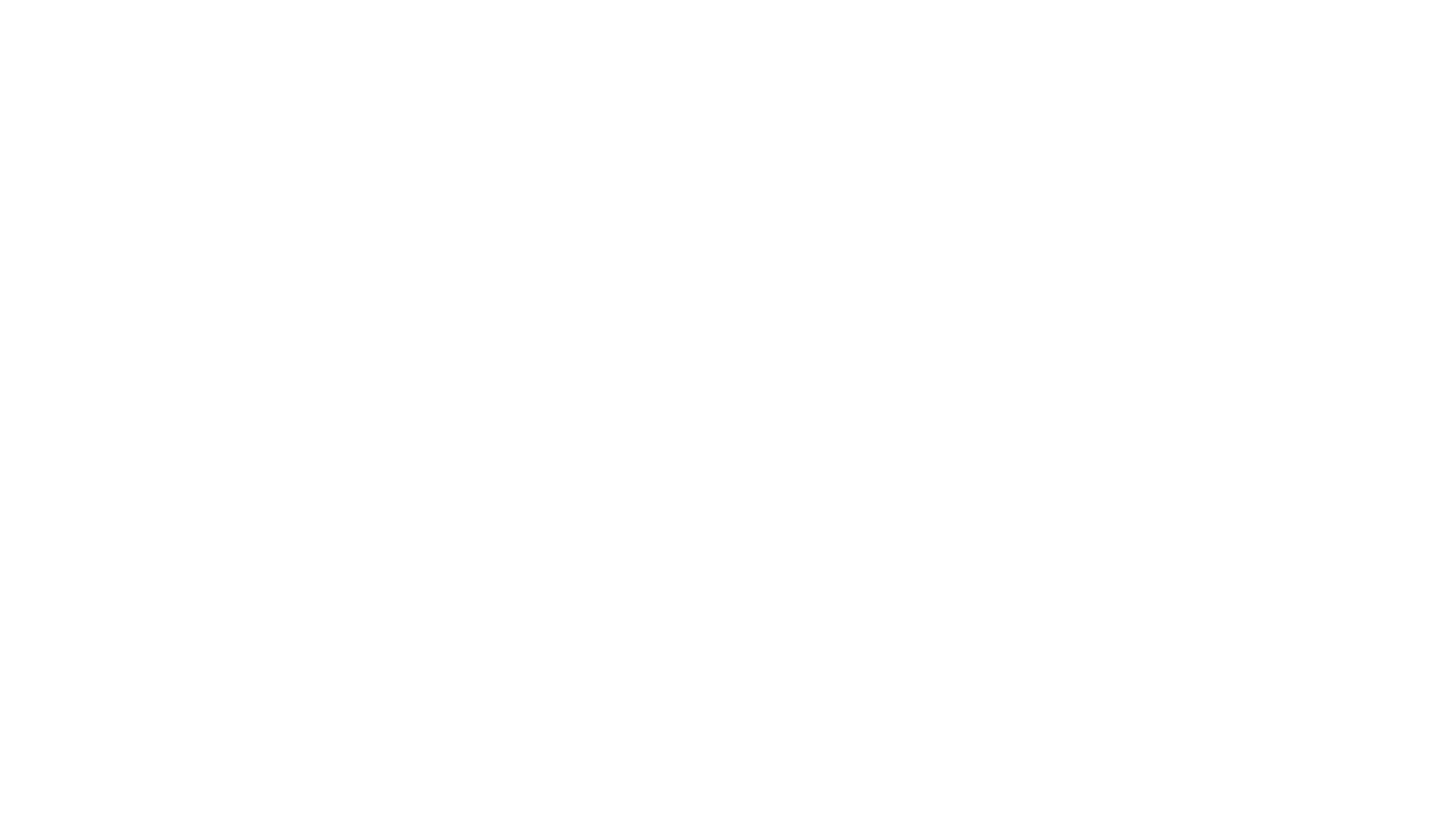Oleh Makmur Idrus
“Capek berkelahi. Tidak ada yang menang, yang ada hanya luka dan penjara. Sekarang saatnya cari kerja, cari masa depan.”
Kalimat sederhana itu diucapkan seorang tokoh pemuda dalam momentum rekonsiliasi Tallo–Bontoala. Namun, kekuatannya jauh melebihi ribuan imbauan resmi. Di balik kata-kata itu tersimpan jeritan generasi yang lelah hidup dalam lingkaran konflik turun-temurun.
Kita semua tahu, Tallo dan Bontoala sudah lama menjadi episentrum perang kelompok di Makassar. Bentrokan demi bentrokan diwariskan dari kakak ke adik, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lorong-lorong sempit di dua kecamatan ini lebih sering menjadi arena perang daripada ruang bermain. Batu, busur, dan parang terasa lebih akrab dibanding buku sekolah dan peralatan kerja. Potret ini bukan sekadar persoalan kriminal, melainkan luka sosial yang mencoreng wajah kota.
Karena itu, langkah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin patut diapresiasi. Ia tidak hanya memimpin rekonsiliasi simbolik, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang lebih konkret: pelatihan keterampilan seperti barista, mekanik, dan menjahit; kegiatan olahraga untuk menyalurkan energi muda; pemberdayaan ibu rumah tangga; hingga rencana pembentukan Creative Hub sebagai wadah kreatif anak muda Tallo dan Bontoala.
Rekonsiliasi yang melibatkan tokoh pemuda dari kedua belah pihak merupakan terobosan penting. Mereka adalah aktor utama di lapangan, yang mampu menggerakkan teman-temannya. Ketika pemuda bersedia duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, dan mulai merancang masa depan bersama, api permusuhan perlahan bisa dipadamkan dari dalam. Suara “capek berkelahi” adalah tanda jelas bahwa generasi muda ingin keluar dari lingkaran dendam, asalkan tersedia ruang dan peluang baru.
Dalam teori konflik, Johan Galtung membedakan negative peace—damai semu, sekadar berhenti berkelahi—dengan positive peace—damai sejati yang ditopang keadilan sosial. Selama ini, perdamaian di Makassar cenderung berhenti pada negative peace: jabat tangan, foto bersama, lalu seminggu kemudian bentrokan kembali pecah. Yang dibutuhkan Tallo dan Bontoala adalah positive peace melalui transformasi sosial: membuka lapangan kerja, memperkuat pendidikan, membangun jembatan sosial, dan menghadirkan masa depan bagi pemuda.
Wali Kota sudah menyalakan api awal transformasi itu. Namun, api hanya akan bertahan bila dijaga bersama: pemerintah, aparat, tokoh agama, keluarga, hingga masyarakat. Program yang dijanjikan tak boleh berhenti di atas kertas. Ia harus benar-benar hadir di lorong-lorong, menyentuh langsung kehidupan pemuda yang selama ini terjebak dalam budaya konflik.
Makassar terlalu besar untuk terus dipenjara stigma sebagai “kota tawuran.” Jika Tallo dan Bontoala—selama ini pusat konflik—berhasil ditransformasi, maka seluruh wajah kota akan ikut berubah. Rekonsiliasi ini harus tercatat bukan sebagai seremoni sesaat, melainkan sebagai titik balik sejarah: dari lorong konflik menuju lorong harapan, dari energi destruktif menjadi energi kreatif, dari dendam menjadi peradaban.