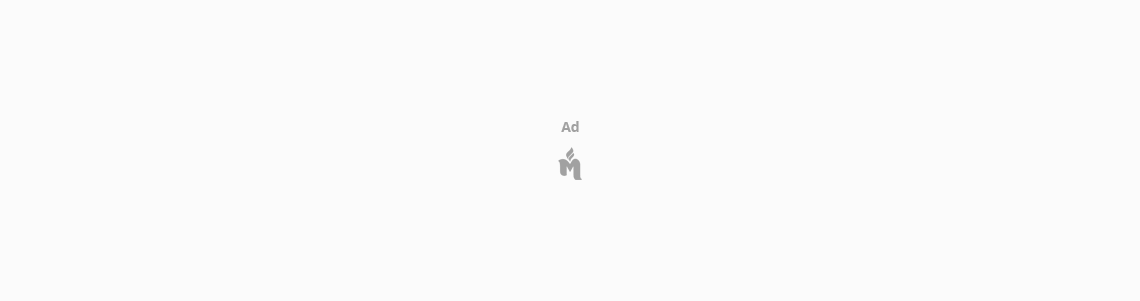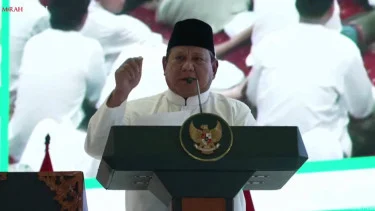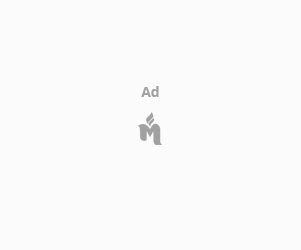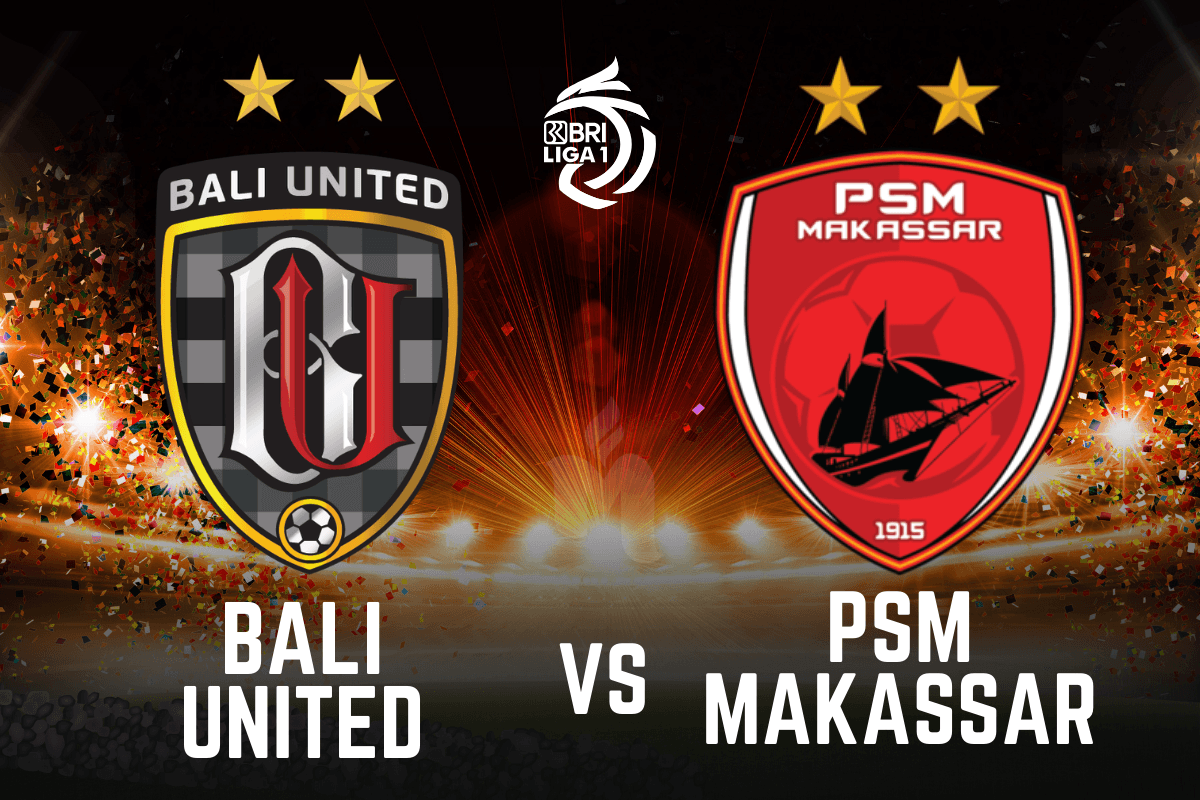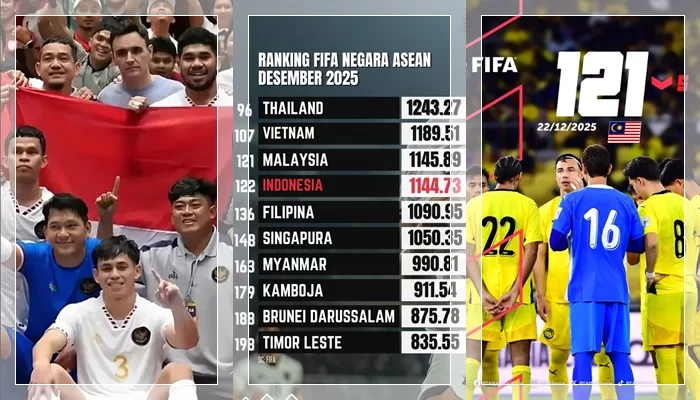Manyala.co – Fenomena toxic relationship semakin banyak dialami generasi Z di Indonesia, dengan pola berulang mulai dari penyangkalan, ketergantungan emosional, hingga keberanian untuk keluar dari hubungan tidak sehat, berdasarkan penuturan sejumlah korban.
Cerita mengenai hubungan yang merugikan secara emosional, verbal, hingga seksual kerap muncul di media sosial dan ruang publik. Pola yang paling sering ditemui adalah siklus kekerasan, permintaan maaf, pemberian perhatian, lalu pengulangan perilaku bermasalah. Situasi ini membuat banyak korban sulit menyadari bahwa hubungan yang dijalani telah berubah menjadi tidak sehat.
Sejumlah individu mengaku tidak langsung menyadari kondisi tersebut. Ada yang menilai pasangannya “sebenarnya baik” meskipun kerap melelahkan secara emosional. Ada pula yang memahami hubungannya bermasalah, tetapi tetap bertahan karena takut kehilangan, takut kesepian, atau berharap pasangan akan berubah.
SA, seorang perempuan yang masih berada dalam hubungan penuh konflik, menggambarkan relasinya sebagai rumit dan sarat perdebatan. Ia menyebut masalah sering muncul tanpa sebab yang jelas, meski dirinya merasa tidak melakukan kesalahan. “Padahal aku ngerasa aku ngga ngapa-ngapain, tapi pasti selalu ada aja yang bikin ribut dan debat, sampai ujung-ujungnya ngajak putus,” kata SA. Meski demikian, ia belum sepenuhnya mengakui hubungannya sebagai toxic dan masih berencana melanjutkan hubungan ke tahap lebih serius.
Kasus lain dialami C, yang telah menjalin hubungan hampir enam tahun. C menyadari hubungannya tidak lagi memberikan rasa aman dan nyaman. Ia menyebut hubungan tersebut terasa hampa, dipenuhi rasa cemas, curiga, dan kecewa. Perselingkuhan berulang menjadi tanda paling jelas, disertai sikap obsesif pasangan dan pengabaian terhadap perasaan C.
Situasi semakin memburuk ketika perselingkuhan pasangannya terbongkar, namun perilaku tersebut tetap berlanjut. Dari pengalaman dan refleksi diri, C akhirnya menyadari bahwa dirinya terjebak dalam toxic relationship dan bertekad keluar dari hubungan tersebut. “Hubungan sehat buat aku itu yang bisa jujur, terbuka, saling menghargai, dan punya batasan yang jelas. Aku cuma pengen sama orang yang lurus,” kata C.
Berbeda dengan SA dan C, AS dan AR merupakan contoh individu yang berhasil keluar dari hubungan tidak sehat. AS memandang toxic relationship sebagai relasi yang kehilangan keseimbangan dan rasa saling menghargai. Menurutnya, manipulasi kerap muncul dengan balutan sikap manis di awal hubungan. “Pinter-pinter pilih pasangan, jangan gampang kegoda bujuk rayu yang keliatannya romantis,” ujar AS.
Pengalaman tersebut membuat AS lebih berhati-hati dan menekankan pentingnya kesadaran sejak awal, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap romantisasi hubungan. Sementara itu, AR menyadari hubungannya bermasalah ketika diminta melakukan hal-hal yang melanggar batas pribadi, termasuk permintaan mengirimkan gambar tidak senonoh.
AR memutuskan mengakhiri hubungan setelah menyadari adanya ketimpangan kekuasaan dan kontrol. Menurutnya, dominasi dalam hubungan hanya dapat diterima jika tidak berubah menjadi perendahan atau paksaan. “Hubungan itu ngga boleh timpang sebelah. Kalau cuma satu pihak yang berkuasa, itu udah ngga sehat,” kata AR.
Pengalaman para Gen Z ini menunjukkan bahwa toxic relationship tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Pola manipulasi emosional, kontrol halus, dan normalisasi perilaku bermasalah sering kali membuat korban bertahan lebih lama. Hingga kini, belum ada data nasional resmi yang merinci prevalensi toxic relationship di kalangan generasi muda, namun kesaksian ini menegaskan urgensi literasi hubungan sehat di ruang publik.