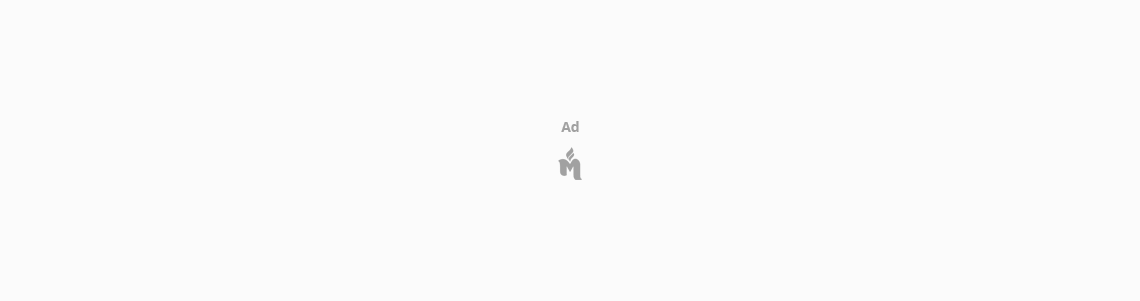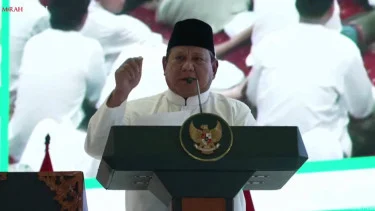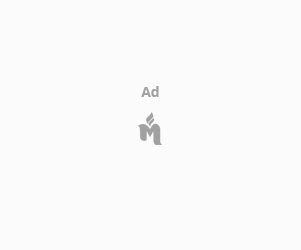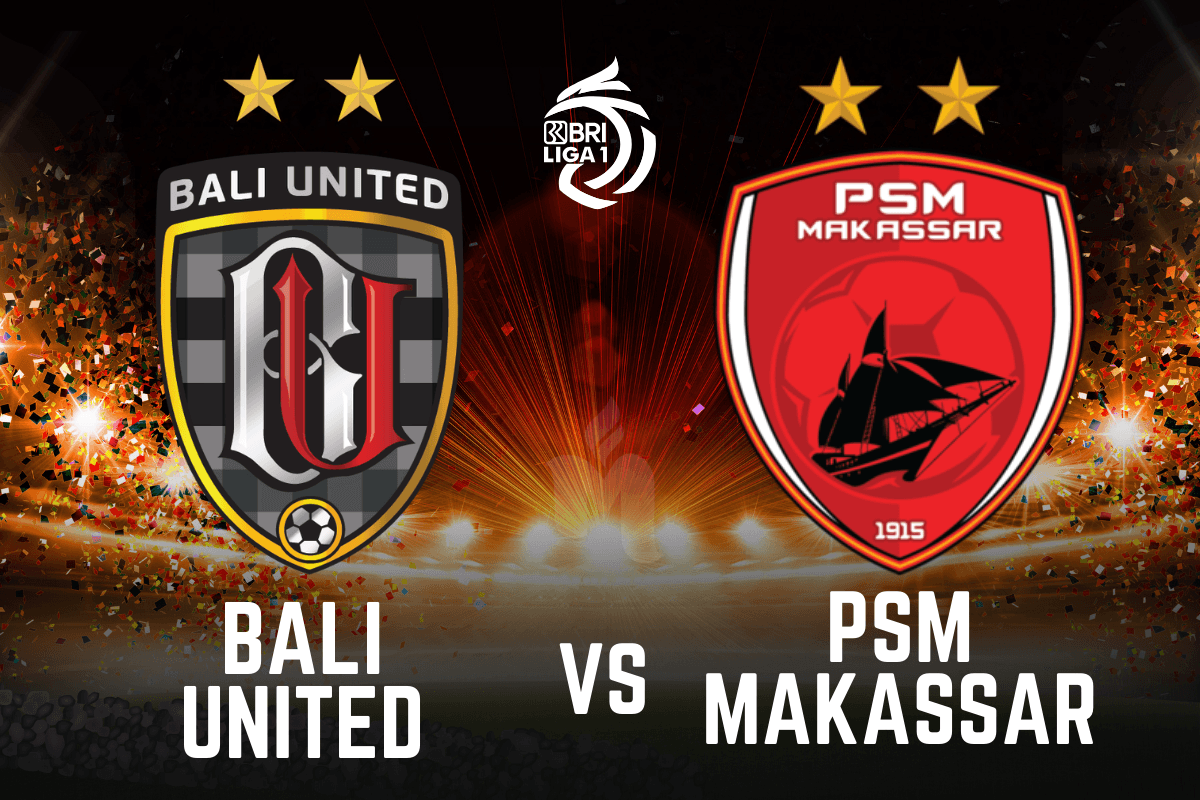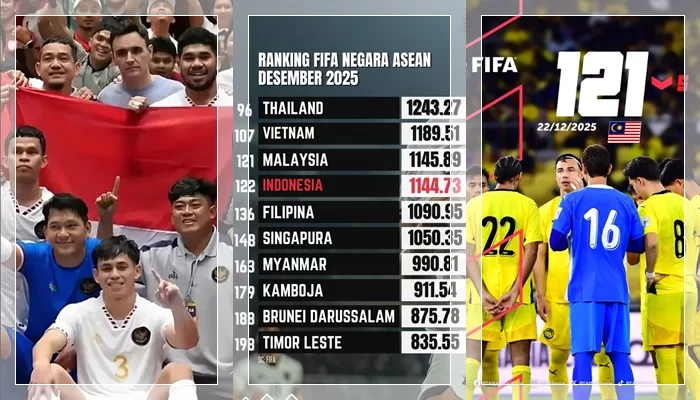Manyala.co – Dampak disrupsi digital dan pandemi COVID-19 masih menghantui industri penyiaran radio di Indonesia. Ratusan stasiun radio swasta terpaksa tutup, sementara yang bertahan menghadapi tekanan berat dari kewajiban royalti musik yang dinilai tidak proporsional. Di tengah kondisi ini, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), pengelola restoran, serta pelaku industri radio dan hiburan lainnya.
Ketua Umum PRSSNI, M. Rafiq, menilai kebijakan pemungutan royalti musik saat ini tidak lagi relevan dengan kondisi industri penyiaran yang telah berubah drastis sejak pandemi. Ia menyebut, tarif royalti sebesar 1,15 persen dari omzet tahunan yang dibebankan kepada radio swasta sangat membebani, terlebih ketika sebagian besar pelaku industri radio kesulitan mencetak keuntungan. “Sebelum pandemi, anggota kami tercatat sekitar 800 stasiun radio. Sekarang yang masih bertahan hanya 600. Itu berarti ada 200 radio yang tutup,” ungkap Rafiq dalam siaran langsung di Radio Suara Surabaya, Selasa (5/8/2025).
Yang menjadi sorotan adalah metode penetapan tarif royalti yang menurut Rafiq didasarkan pada acuan lama, yakni periode 2016–2019. Ia mempertanyakan keabsahan tagihan yang dikeluarkan LMKN saat ini jika belum ada pembaruan dasar hukum atau ketentuan tarif terbaru. “Kalau sekarang LMKN menagih, dasarnya tahun berapa? Tarif itu hanya berlaku sampai 2019,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rafiq mengkritik mekanisme pembayaran yang dinilai tidak hanya memberatkan secara nominal, tetapi juga secara administratif. Radio swasta, katanya, harus menjalani audit keuangan oleh akuntan publik terlebih dahulu sebelum besaran royalti ditentukan dari omzet mereka. “Jadi kami ini dua kali bayar. Pertama untuk audit laporan keuangan, lalu kedua untuk royalti musik berdasarkan omzet yang diaudit itu,” paparnya.
Sebagai solusi konkret, PRSSNI mengusulkan agar skema pembayaran royalti untuk radio tidak lagi dihitung berdasarkan omzet tahunan, melainkan menggunakan sistem tarif flat yang lebih terjangkau. Rafiq menyampaikan bahwa usulan tersebut sudah pernah diajukan sejak tahun 2020, namun belum mendapatkan tanggapan resmi. Dalam usulan itu, PRSSNI membagi kategori radio berdasarkan wilayah operasional. Untuk radio kelas A yang berada di Ibu Kota negara, tarif royalti diusulkan sebesar Rp1,5 juta per tahun. Radio kelas B di Ibu Kota provinsi diusulkan membayar Rp1 juta per tahun, sedangkan radio kelas C yang beroperasi di kabupaten/kota cukup dikenakan Rp100 ribu per tahun.
Menurut Rafiq, pendekatan ini akan jauh lebih adil dan realistis, mengingat mayoritas radio di Indonesia saat ini berada di ambang kerugian. “Data kami menunjukkan, dari 600 radio aktif saat ini, tidak sampai 10 persen yang betul-betul mencetak profit,” ujarnya. Bahkan, banyak di antaranya terpaksa mengurangi jumlah karyawan, merelokasi kantor ke ruang yang lebih kecil, hingga menurunkan daya pancar siaran untuk menekan biaya operasional.
Ia juga menyoroti ketimpangan perlakuan antara radio komersil dan non-komersil. Saat ini, radio non-komersil hanya dikenakan tarif royalti tetap sebesar Rp2 juta per tahun, tanpa memperhatikan omzet atau pendapatan. PRSSNI menilai klasifikasi semacam itu kurang adil, dan mendorong agar perhitungan royalti tidak lagi berdasarkan status radio komersil atau non-komersil. Sebagai gantinya, Rafiq mengusulkan pendekatan berbasis wilayah dan cakupan siaran.
Dalam konteks hukum, Rafiq merujuk pada UU Penyiaran yang mengklasifikasikan radio ke dalam empat kategori: publik, swasta, pemerintah, dan komunitas. Oleh karena itu, ia berharap pengaturan tarif royalti juga dapat disesuaikan dengan klasifikasi ini, dan tidak menyamaratakan seluruh radio sebagai entitas komersial.
Secara keseluruhan, PRSSNI meminta agar kebijakan royalti tidak diberlakukan secara sepihak tanpa memahami kondisi lapangan. Mereka ingin adanya pertemuan formal yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan keseimbangan antara hak pelaku industri musik dan kelangsungan hidup media penyiaran radio. “Kami tidak menolak membayar royalti. Tapi kami ingin kebijakan yang adil, proporsional, dan realistis,” tutup Rafiq.